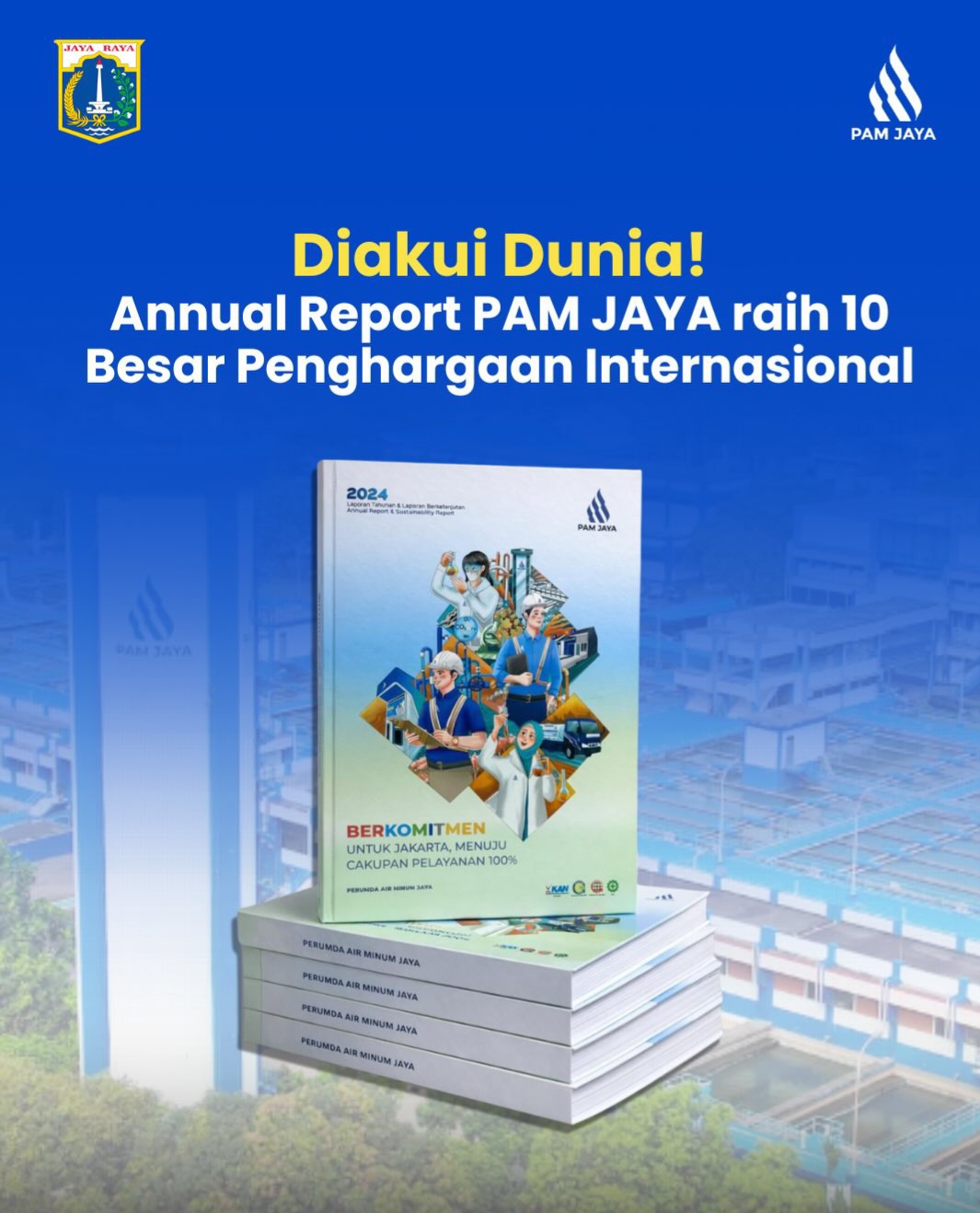Krisis Makna di Balik Identitas Starbucks di Era Digital
Reporter:
PorosBumi
22 Jan 2026, 17:26:22 WIB

Fathiyah Azzahra
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta
DALAM beberapa tahun terakhir, reputasi merek global tidak lagi ditentukan semata oleh kualitas produk atau layanan. Di era digital, reputasi semakin dibentuk oleh bagaimana publik menafsirkan nilai, sikap, dan posisi moral sebuah perusahaan.
Fenomena ini terlihat jelas pada tekanan reputasi yang dialami Starbucks, yang di sejumlah negara termasuk Indonesia, menghadapi kritik dan ajakan boikot.
Dalam gelombang boikot global yang dikenal sebagai gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), Starbucks muncul sebagai salah satu merek yang paling disorot. CNBC Indonesia melaporkan bahwa Starbucks sempat dihapus dari daftar resmi target boikot gerakan BDS, namun persepsi negatif di sebagian publik tetap bertahan (CNBC Indonesia, 2024).
Dalam menghadapi tekanan publik, Starbucks juga menyampaikan pernyataan resmi melalui kanal komunikasinya di Indonesia. Perusahaan menegaskan tidak terlibat dalam konflik atau agenda politik tertentu, sekaligus menekankan komitmen pada nilai kemanusiaan. Pernyataan ini merupakan upaya klarifikasi posisi korporasi, meski dalam konteks krisis reputasi.
Reputasi tidak dibangun oleh klarifikasi sepihak perusahaan, tetapi oleh akumulasi persepsi publik yang berkembang di ruang sosial. Hal ini terlihat dari dinamika boikot Starbucks yang tidak sepenuhnya mengikuti klarifikasi perusahaan.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Starbucks bukan sekadar isu viral di media sosial, melainkan krisis reputasi dan kepercayaan. Krisis ini berakar pada benturan antara identitas merek global yang berbasis nilai dan ekspektasi moral publik yang semakin tinggi.
Dalam komunikasi korporasi, reputasi tidak identik dengan citra sesaat. Reputasi terbentuk dari akumulasi persepsi publik dalam jangka panjang. Paul A. Argenti menekankan bahwa reputasi perusahaan bukan ditentukan oleh apa yang dikatakan perusahaan tentang dirinya, melainkan oleh apa yang diyakini publik berdasarkan pengalaman, pemberitaan media, dan percakapan sosial. Dengan kata lain, klarifikasi faktual saja tidak cukup ketika krisis terjadi di ranah makna dan kepercayaan.
Tekanan reputasi terhadap Starbucks tidak dapat dilepaskan dari identitas merek yang selama ini dibangun sebagai ethical brand yang menjunjung nilai keberlanjutan, inklusivitas, dan tanggung jawab sosial. Identitas berbasis nilai ini, dalam kerangka Argenti, membentuk company character yang kuat.
Namun, karakter yang normatif justru meningkatkan ekspektasi publik. Ketika publik memandang respons perusahaan terhadap isu global tidak sejalan dengan nilai yang dikomunikasikan, identitas tersebut berbalik menjadi titik rawan reputasi. Inilah yang menjelaskan mengapa merek seperti Starbucks lebih rentan dibanding merek yang sejak awal tidak mengklaim posisi moral tertentu.
Namun, identitas yang kuat juga membawa konsekuensi reputasional. Semakin normatif nilai yang diklaim perusahaan, semakin tinggi pula ekspektasi publik terhadap konsistensinya. Ketika publik menilai respons perusahaan terhadap isu global tidak sejalan dengan nilai yang selama ini dikomunikasikan, maka identitas tersebut justru berubah menjadi titik kerentanan reputasi.
Argenti membedakan secara tegas antara corporate brand dan corporate reputation. Brand adalah janji implisit perusahaan tentang siapa mereka dan bagaimana mereka bertindak. Reputasi adalah hasil penilaian publik atas janji tersebut.
Pada Starbucks, klaim sebagai perusahaan yang etis dan peduli sosial bersinggungan dengan tuntutan publik yang semakin politis dan bermuatan moral. Respons komunikasi yang cenderung normatif dan defensif dengan menekankan posisi tidak terlibat langsung, boleh jadi aman secara legal, tetapi tidak sepenuhnya menjawab persoalan reputasi.
Ruang digital mempercepat eskalasi krisis reputasi melalui penyederhanaan isu kompleks menjadi simbol. Dalam konteks konflik Gaza 2023–2024, tagar #BoycottStarbucks dilaporkan meraih jutaan interaksi di berbagai platform media sosial, menjadikan Starbucks simbol dari narasi yang lebih besar tentang kapitalisme global dan keberpihakan moral (lihat ringkasan liputan protes global dalam berbagai laporan media internasional).
Dalam situasi seperti ini, perusahaan kehilangan kontrol atas narasi tentang dirinya sendiri, sebagaimana ditegaskan Argenti bahwa di era digital, reputasi dibentuk lebih cepat oleh percakapan publik dibandingkan oleh pesan resmi perusahaan.
Kasus Starbucks menunjukkan bahwa krisis reputasi di era digital tidak selalu berangkat dari kesalahan operasional, melainkan dari kegagalan mengelola makna dan ekspektasi publik secara berkelanjutan. Klarifikasi faktual yang defensif mungkin memadai secara hukum, tetapi belum tentu efektif secara reputasional.
Bagi merek berbasis nilai, tantangan komunikasi korporasi ke depan bukan lagi sekadar menyampaikan pesan yang benar, melainkan menjaga keselarasan antara identitas, brand, dan persepsi publik di tengah lanskap digital yang semakin politis dan emosional.
Untuk memulihkan kepercayaan, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih strategis. Pertama, dari sisi komunikasi internal, perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan memahami posisi dan nilai organisasi secara utuh. Di era digital, karyawan adalah duta reputasi informal yang berinteraksi langsung dengan publik. Ketidaksiapan internal berpotensi memperbesar krisis eksternal.
Kedua, pada ranah komunikasi eksternal, perusahaan perlu bergerak melampaui pernyataan defensif. Pendekatan dialogis yang mengakui kompleksitas isu dan menjelaskan keterbatasan peran korporasi secara terbuka cenderung lebih kredibel dibandingkan narasi normatif yang kaku.
Transparansi parsial sering kali lebih dipercaya daripada klaim sempurna.
Ketiga, dari sisi tata kelola, nilai-nilai yang dikomunikasikan harus terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam komunikasi krisis. Nilai tidak boleh berhenti sebagai narasi pemasaran, melainkan menjadi pedoman manajerial yang nyata. Tanpa integrasi ini, komunikasi berbasis nilai berisiko dipersepsikan sebagai simbolik.
Pada akhirnya, dinamika reputasi yang dialami Starbucks memberi pelajaran penting bahwa reputasi korporasi di era digital tidak lagi dapat dikelola semata sebagai persoalan komunikasi, tetapi sebagai bagian dari relasi sosial yang terus dinegosiasikan.
Publik hari ini tidak hanya menilai apa yang dikatakan perusahaan, melainkan bagaimana perusahaan memaknai posisinya di tengah perubahan nilai dan sensitivitas sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, komunikasi korporasi dituntut untuk lebih rendah hati, adaptif, dan berorientasi jangka Panjang, bukan sekadar menjaga citra, tetapi merawat kepercayaan.
Reputasi, pada akhirnya, bukan soal seberapa keras perusahaan berbicara tentang nilai, melainkan seberapa konsisten nilai itu tercermin dalam sikap, keputusan, dan cara perusahaan hadir di ruang publik.

1.jpg)


.jpg)