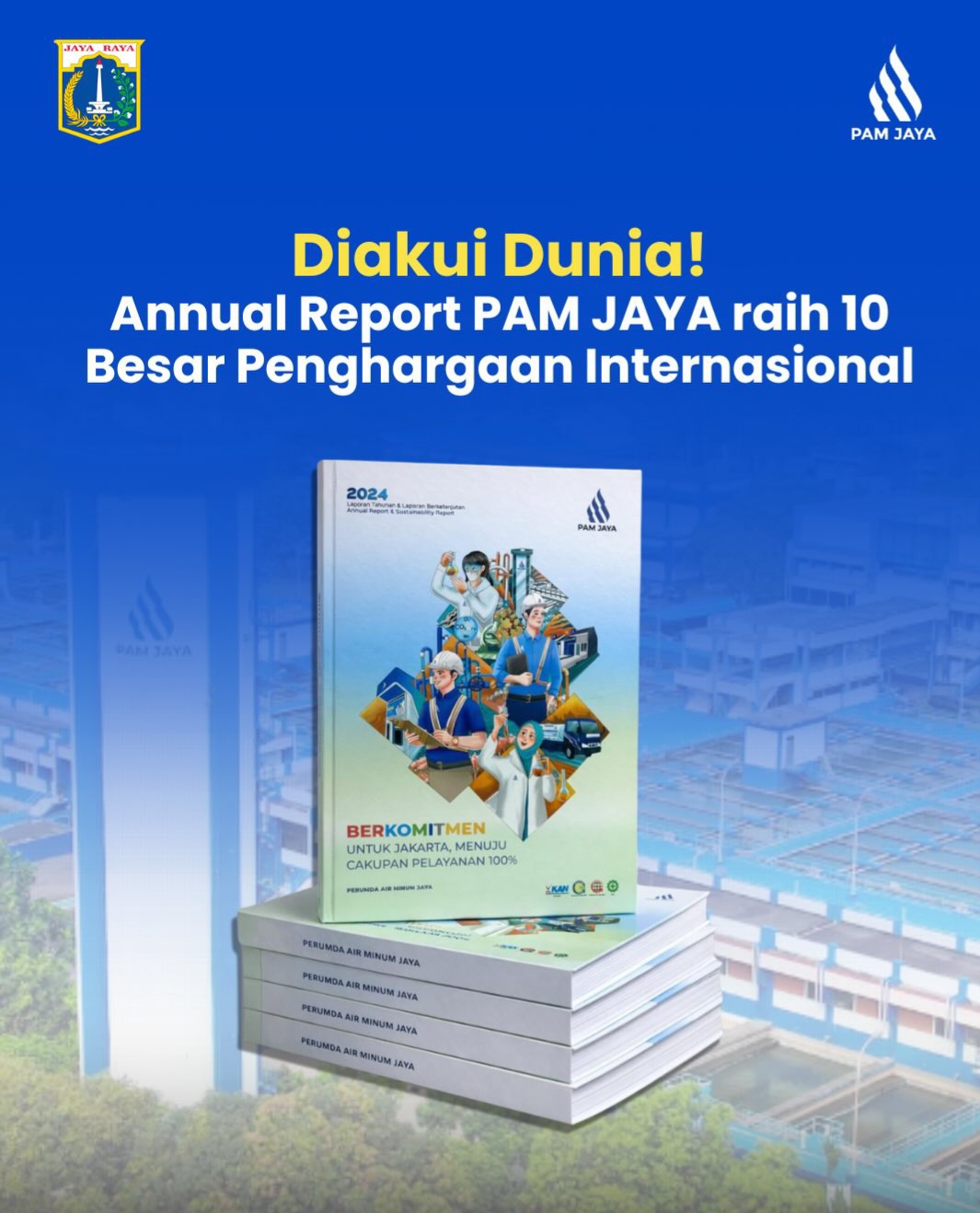Rumah: Kekuasaan dan Kenangan
.jpg)
Bandung
Mawardi
Tukang kliping,
bapak rumah tangga
Baca Juga
POLITIK dimulai dari rumah. Kita mengingat
rumah-rumah masa lalu menjadi tempat untuk obrolan mengenai beragam gagasan
dalam arus politik. Di rumah, para tokoh berpikir dan membuat tulisan-tulisan.
Rumah memang berurusan keluarga. Berdiam di rumah masih memungkinkan
membadaikan ide-ide dalam menanggapi politik-kolonial atau angan pembentukan
(negara) Indonesia.
Kita mengingat
rumah-rumah (bersejarah) dihuni HOS Tjokroaminoto, MH Thamrin, Tjipto
Mangoenkoesoemo, Radjiman Wediodiningrat, dan lain-lain. Rumah itu
kadang-kadang kedatangan tamu, Para tokoh berkumpul dalam kepentingan mencari
mufakat atau debat disempurnakan minum teh atau kopi dengan selingan makanan.
Rumah-rumah
belum ingin dibakukan sebagai “institusi politik” tapi kesadaran atas
nasionalisme, modernitas, “kemadjoean”, sebaran iman, atau pencerahan
pendidikan bertumbuh dan bergulir diberkati oleh matahari, bulan, dan bintang.
Di setiap hari, rumah-rumah dalam putaran waktu pun menimbulkan putaran
gagasan.
Sekian hari
lalu, 29 September 2025, Prabowo Subianto berpidato tentang rumah. Kita
menganggap itu tema kecil, tapi Prabowo Subianto lantang menggunakan
diksi-diksi besar. Pidato mengakibatkan rumah menjadi penentuan derajat
penguasa dan “pembenaran” atas politik memihak kaum miskin. Kita tak mengira
Prabowo Subianto menggebu saat memasalahkan rumah setelah “malapetaka” rumah
bersumber kebijakan di DPR dan gugatan publik. Konon, Prabowo Subianto ingin
membuktikan komitmen: negara memastikan jutaan orang tak mampu dapat menggapai
sejahtera dan memenuhi kebutuhan papan (rumah).
Pihak pemerintah
mengabarkan telah berhasil mengadakan 26 ribu rumah bersubsidi. Kerja besar
tapi berlangsung cepat dan “mendesak”. Kita boleh kagum atau “merem” memikirkan
kesaktian para menteri dan pejabat dalam mewujudkan rumah. Mereka tak mencipta
dongeng tapi melaksanakan pekerjaaan mendapat pujian Prabowo Subianto dan tepuk
tangan ribuan orang.
Prabowo Subianto
tampak semringah. Rumah telah memberi “kepastian” atas perwujudan segala misi
dalam janji-janji awal saat menjadi penguasa. Acara besar diselenggarakan agar
tercipta narasi sejarah mengenai Prabowo Subianto dalam menunaikan
politik-rumah. Kunci-kunci rumah telah diberikan kepada ribuan orang. Kita
menanti rumah-rumah mengabarkan dan mengisahkan bahagia, bukan tumpukan keluhan
dan kebingungan atas nasib pada babak-babak lanjutan.
Sejak dulu,
legitimasi penguasa memang dipengaruhi rumah. Pada 1951, Kementerian Penerangan
menerbitkan buku kecil berjudul Perumahan Rakjat. Buku itu dapat kita
baca lagi untuk mengetahui kebijakan pemerintah mengenai rumah dalam ruwet
demokrasi dan galak revolusi.
Kita membaca
keterangan: “Di zaman negara kita merdeka ini perumahan rakjat seharusnja
disesuaikan dengan suasana rakjat jang merdeka. Direntjanakan bahwa rumah-rumah
jang akan dibuat itu semua adalah pasangan batu, jang dengan mudah dapat
dibersihkan. Dalam rumah pasangan batu itu rakjat kita akan terpaksa mempunjai
perasaan untuk menjesuaikan nafkahnja dengan keadaan. Hal ini dapat
dimengerti.”
Pada masa
1950-an, Indonesia masih sering bercerita tentang rumah-rumah penduduk dibuat
dari bambu atau papan. Pertumbuhan kota dengan kedatangan orang-orang dari desa
ikut mencipta permukiman kumuh atau semrawut. Rumah-batu menjadi pemandangan
“menakjubkan” saat Indonesia masih terseok-seok.
Latar sejarah
menjadi dalil atas pembuatan kebijakan perumahan: “Akibat dari
pertempuran-pertempuran karena Perang Dunia II dan revolusi di negara kita,
banjak rumah jang hantjur. Hal ini mengurangkan adanja tempat tinggal, jang
menambah pada sangat penuhnja penggunaan rumah.” Di Indonesia masa 1950-an,
orang atau keluarga mengimpikan rumah. Mereka mengerti situasi politik terus
rumit.
Kemampuan
mencari nafkah tak menjanjikan bisa dikumpulkan untuk membangun atau membeli
rumah (sederhana). Tanggung jawab pemerintah dinantikan agar merdeka
mendapatkan makna. Buku itu menggoda kita membuat perbandingan politik-rumah di
Indonesia, sejak masa kekuasaan Soekarno sampai Prabowo Subianto. Kita pun
memerlukan mengetahui kemunculan dan perkembangan tugas-tugas dalam kementerian
perumahan, dari masa ke masa.
Lelah menggurui
kekuasaan dan rumah, kita di pinggiran dulu untuk menikmati imajinasi rumah
melalui lagu-lagu. Pilihan mendengar lagu merdu diniatkan “tandingan” atas
pidato-pidato Prabowo Subianto. Kita kadang memilih menikmati merdu ketimbang
omongan menggebu.
Lagu bermutu
pantas mendapat telinga saat Indonesia makin berisik dibawakan oleh Sal Priadi
berjudul “Kita Usahakan Rumah Itu”. Pendengar mendapat imajinasi sederhana tapi
sadar harga tanah makin mahal. Ongkos membuat rumah juga besar. Konon, kaum
muda masa sekarang sedang takut dan rela tak menikah. Mereka dibuat bingung
oleh keterbatasan anggaran demi menghuni rumah. Pernikahan, anak, dan perunaham
kadang jadi paket pemicu pusing kuadrat.
Kata-kata
terdengar di telinga: Kita usahakan rumah itu/ Dari depan akan tampak
sederhana/ tapi kebunnya luas/ Tanamannya mewah, megah// Kita usahakan rumah
itu/ Dari depan akan tampak sederhana/ tapi dibuat kuat, lega. Penampilan rumah
telah terimajinaskan. Pencantuman “sederhana” bisa berarti kejujuran atau
kegagalan mengerti gagasan sederhana pernah disampaikan pada masa kekuasaan
Soekarno dan Soeharto. Pada masa Orde Baru, kita teringat kebijakan rumah
sederhana atau rumah sangat sederhana.
Rumah bukan
sekadar urusan anggaran. Sal Priadi bersenandung: Urusan perabot dan
wangi-wangian/ kuserahkan pada seleramu yang lebih maju/ Tapi tata ruang, aku
ikut pertimbangkan/ karena kalau nanti kita punya kesibukan// Malam tetap
kumpul di meja panjang/ ruang makan kita/ berbincang tentang hari yang panjang.
Di rumah, ada peristiwa-peristiwa. Kita berimajinasi penghuni rumah memiliki
peristiwa dan membuat arti secara bersama. Rumah bukan selesai sebagai tempat
untuk makan dan tidur. Imajinasi tak tersampaikan oleh Prabowo Subianto atau
para menteri. Mereka melaksanakan kebijakan, bukan pencipta cerita.
Kita
mengandaikan orang-orang menghuni rumah atas tanggung jawab pemerintah. Mereka
berharap betah dan mampu mencipta makna-makna selama berada di rumah. Jalinan
pemerintah dan rumah tak membuat mereka harus selalu setuju dengan langkah dan
arah pemerintah. Di rumah, mereka boleh “berpolitik” mengacu tokoh, kejadian,
dan situasi terus berkembang di Indonesia. Rumah tetap saja politis.
Rumah pun puitis
saat kita agak melupakan pemerintah. Kita mengingat Rendra saja. Pada masa Orde
Baru, Rendra sering menggubah puisi-puisi menggugat pemerintah atau menanggapi
renik-renik kekuasaan. Ia pun sering sodorkan puisi romantis agar para pembaca
kerasan hidup di Indonesia. Kita mendingan mengingat puisi-puisi lawas, sebelum
rezim Orde Baru tegak mengusung gagasan rumah sederhana dan keluarga bahagia.
Kita membuka
buku berjudul Empat Kumpulan Sadjak (1961). Para pembaca silam ingat ada
masalah kawin, iman, kota, dan rumah dalam sekian puisi Rendra. Kita membaca
puisi berjudul “Kenangan dan Kesepian”. Puisi menjauh dari urusan dan dikte
pemerintah. Pembaca boleh terlena dan cemburu: Rumah tua/ dan pagar batu/
Langit di desa/ sawah dan bambu// Berkenalan dengan sepi/ pada kejemuan
disandarkan dirinya/ Jalanan berdebu tak berhati/ lewat nasib menatapnya. Kita
berimajinasi rumah dalam kenangan itu dihuni keluarga berlatar masa kolonial
atau 1950-an.
Rumah tak
bercerita perang. Rumah tanpa panji dan pekik demi revolusi. Rumah itu
perasaan-perasaan, Rendra menulis: Cinta yang datang/ burung tak tergenggam/
Batang baja waktu lengang/ dari belakang menikam// Rumah tua/ dan pagar batu/
Kenangan lama/ dan sepi yang syahdu. Orang tinggal di rumah membuat
kenangan-kenangan. Orang meninggalkan rumah membawa kenangan-kenangan. Orang
kembali ke rumah berarti membenarkan kenangan-kenangan. Rendra menganggap rumah
itu dunia penuh kemungkinan dalam mengadakan album sendiri dan bersama. Begitu.

1.jpg)


.jpg)